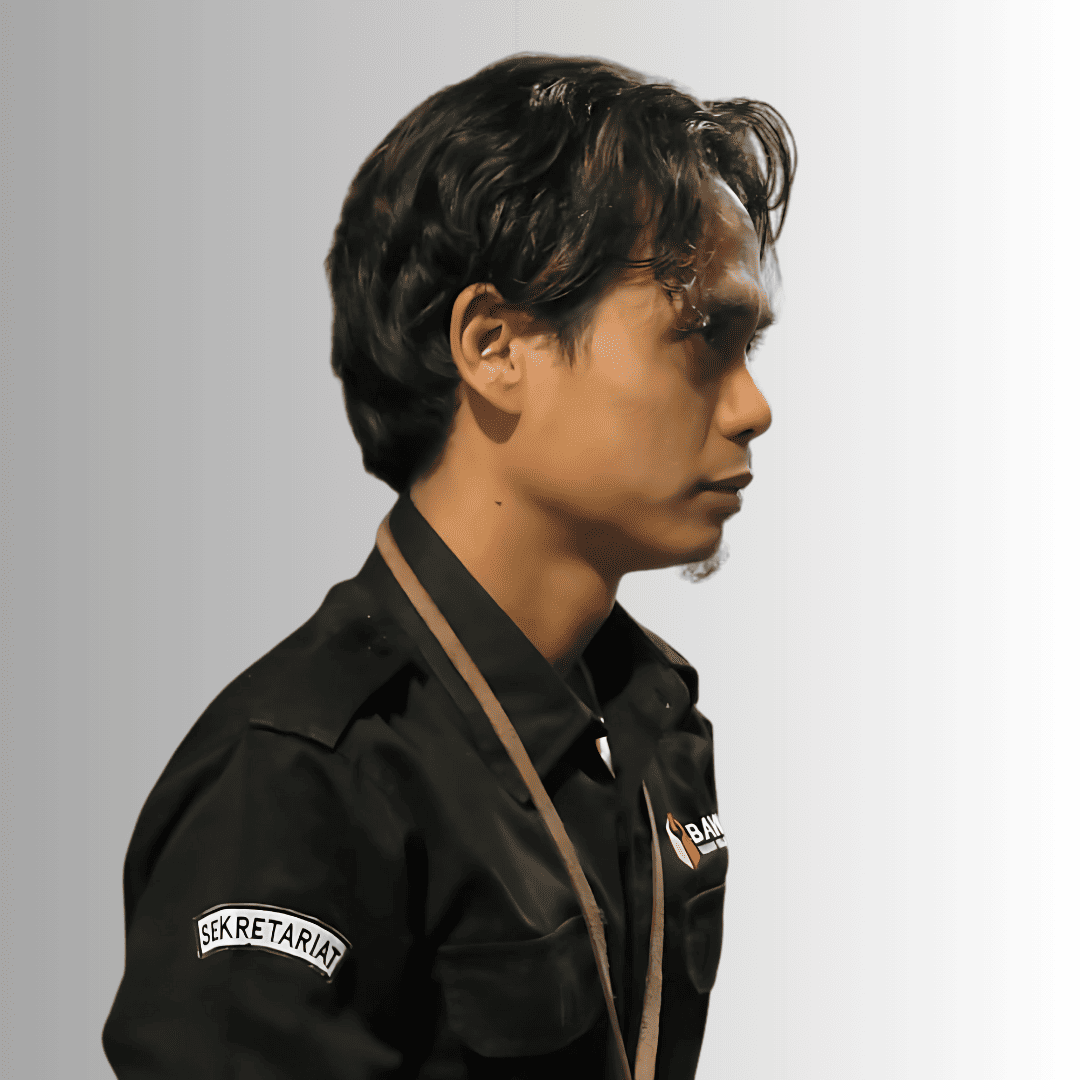DEMOKRASI: LAHAN PENGABDIAN, BUKAN PEKERJAAN BARU
|
Gelombang demokrasi yang menerpa Indonesia selama 21 tahun terakhir membawa angin segar sekaligus teka-teki. Di tengah euforia kebebasan pasca rezim Orde Baru, demokrasi kerap disalahtafsirkan sebagai pasar bebas kuasa. Padahal, hakikatnya adalah ruang pengabdian.
Eksperimen Kekuasaan Dua Zaman
Orde Baru membangun negeri dengan paradigma tunggal: stabilitas politik adalah fondasi kemajuan ekonomi. Dua dekade (1970-1990) dihabiskan untuk merancang sistem teknokratis yang memagari partisipasi rakyat. Partai politik disederhanakan bagai orkestra dengan satu partitur, organisasi massa dijinakkan menjadi kepanjangan negara. Trilogi Pembangunan digaungkan, namun kemakmuran hanya mengendap di kantong segelintir elite. Ketimpangan tumbuh subur di balik gemerlap pertumbuhan ekonomi 7%.
Lengsernya Soeharto pada 1998 menjadi titik balik. Keran demokrasi dibuka lebar. Ratusan partai politik bermunculan bak jamur di musim hujan, pemilu digelar berulang dengan kebebasan belum pernah terjadi. Ruang publik yang dikekang tiga puluh dua tahun tiba-tiba menjadi lapangan raya pemikiran. Inilah Reformasi: saat partisipasi bukan lagi ancaman, melainkan napas kedaulatan.
Partisipasi: Detak Jantung Demokrasi
Dalam teori klasik, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Partisipasi politik menjadi barometer hidup-matinya sistem ini. Di Indonesia pasca-1998, partisipasi itu mewujud dalam dua bentuk: formal melalui lembaga pemantau terakreditasi di KPU/Bawaslu, dan ekstra formal lewat komunitas warga yang mengawal pemilu dengan caranya sendiri. Mereka bagai penjaga mercusuar di tengah lautan kontestasi merekam pelanggaran, mengkritik penyimpangan, memastikan asas Luber-Jurdil tak sekadar slogan.
Namun sejarah pemilu kita menyimpan paradoks. Partisipasi tertinggi justru terjadi di Pemilu 1999 (93%), kemudian terus merosot meski kebebasan semakin luas. Seolah ada kelelahan demokrasi ketika ruang telah terbuka lebar.
Bayang-bayang Pasar Politik
Di balik kemajuan sistem elektoral, bahaya mengintai. Demokrasi mulai berbau transaksional. Partai politik bertransformasi menjadi perusahaan pencari rente, sementara politisi menghitung untung-rugi jabatan bagai pedagang. Uang berbicara di bilik suara, janji jabatan bertebaran, loyalitas diperjualbelikan. Politik tak lagi sekadar pengabdian, melainkan karier yang menjanjikan pundi-pundi kekayaan.
Era digital malah memperumit tantangan. Partisipasi kini juga berarti ribuan like di media sosial, komentar panas di kolom daring, atau gelombang cancel culture. Mudah tersulut, sulit berdialog. Di tengah hiruk-pikuk ini, esensi partisipasi sebagai alat kendali kekuasaan nyaris tenggelam.
Menjaga Kemurnian Niat
Di ujung refleksi ini, penulis berpegang pada keyakinan: demokrasi hanya bermakna ketika dijalani dengan ikhlas. Generasi muda khususnya ditantang untuk tak terjebak dalam logika transaksional. Partisipasi politik harus tetap suci—bukan pekerjaan yang menghitung laba, melainkan pengabdian yang menuntut pengorbanan.
Menjelang Pemilu 2029, kita membutuhkan lebih banyak penjaga nilai. Bukan pencari rente, bukan pedagang pengaruh, melainkan warga yang rela mengawal demokrasi dengan nurani. Karena di tangan merekalah, demokrasi akan tetap menjadi lahan subur pengabdian, bukan tambang emas kekuasaan.
Epilog: Jejak Referensi
Pemikiran dalam tulisan ini bersandar pada karya-karya:
- Miriam Budiardjo (2008, 1982) tentang partisipasi politik
- Huntington & Nelson (1990) mengenai dilema partisipasi di negara berkembang
- Richard Robison (2012) yang mengupas kapitalisme Orde Baru
- Saiful Mujani dkk. tentang perilaku pemilih pasca-Reformasi
- Perludem (2014) perihal pengawasan pemilu oleh masyarakat
Penulis : Surabili
Dokumentasi : Surabili
Editor : Jhonny Sitorus